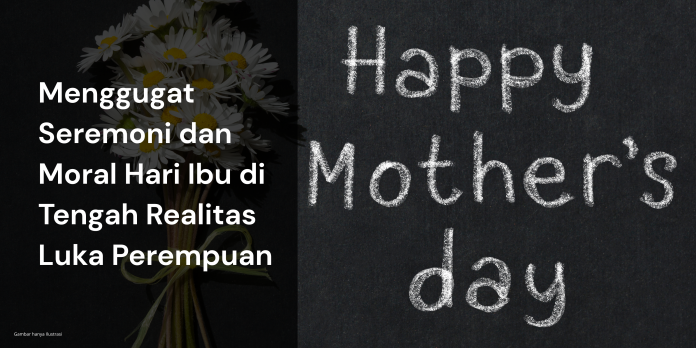Oleh: Tunjung Eko Wibowo
Setiap tanggal 22 Desember, ruang publik kita mendadak riuh oleh ornamen sentimentil. Iklan diskon kado bermunculan, baliho pejabat dengan ucapan selamat terpampang di sudut kota dan linimasa media sosial berubah menjadi galeri foto kenangan bersama Ibu. Kita seolah sedang merayakan sebuah “hari raya” besar yang sakral. Namun, di balik keriuhan seremoni tahunan ini, terselip sebuah paradoks yang sangat menggelisahkan. Apakah kemuliaan seorang Ibu kini telah tereduksi menjadi sekadar komoditas musiman dan instrumen untuk menutupi borok ketidakadilan yang kian menganga?
Dalam perspektif Islam yang progresif dan jernih, memuliakan Ibu bukan sekadar ritual kalender yang bersifat atomistik berdiri sendiri dan terputus dari hari-hari lainnya. Islam tidak mengenal konsep “hari raya” untuk Ibu dalam arti ritual tahunan yang menggugurkan kewajiban di hari-hari lainnya. Sebab di dalam Islam, memuliakan Ibu adalah ibadah harian yang melintasi batas waktu. Hal ini dipertegas dalam Al-Qur’an Surah Al-Isra ayat 23:
“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-k1ali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ‘ah’ dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang 2mulia.” (QS. Al-Isra: 23)
Ayat ini menginstruksikan bakti yang bersifat daily basis atau harian—sebuah pengabdian tanpa jeda. Namun, kenyataan di lapangan hari ini menunjukkan wajah yang berbeda. Hari Ibu terjepit di antara seremoni hambar dan realitas luka perempuan yang sering kali ditutupi atas nama agama dan tradisi.
Tragedi di “Rumah” Agama yang Mengusik Nurani Pesantren
Salah satu luka paling perih yang harus kita akui dengan jujur adalah meningkatnya kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan agama, termasuk pesantren. Sangat ironis ketika institusi yang seharusnya menjadi benteng moral dan tempat paling aman bagi para santriwati calon-calon Ibu masa depan, justru menjadi medan trauma yang menghancurkan masa depan. Kasus pelecehan yang dilakukan oleh oknum pengasuh, guru agama, hingga pemilik pondok pesantren bukan sekadar kejahatan seksual biasa, melainkan pengkhianatan terhadap amanah wahyu Tuhan.
Dalam tradisi Islam yang murni, hubungan guru dan murid adalah hubungan spiritual yang sakral. Namun relasi kuasa yang sangat timpang antara “Kiai” atau “Ustadz” dengan santrinya sering kali disalahgunakan untuk melanggengkan nafsu bejat. Yang lebih menyedihkan adalah fenomena “dinding diam” yang menyertainya. Banyak kasus sengaja ditutupi oleh lingkungan internal dengan dalih menjaga marwah institusi agama atau menjaga aib guru.
Kita harus tegas menyatakan, Menutupi kejahatan seksual bukanlah bagian dari menjaga agama. Islam hadir sebagai pembebas dari kezaliman. Memuliakan perempuan berarti memberikan keadilan hukum yang tanpa pandang bulu kepada pelaku, meski mereka berlindung di balik jubah agama. Membiarkan predator tetap berkuasa dengan dalih “menghormati guru” adalah bentuk penghinaan tertinggi terhadap hak asasi perempuan yang dijamin oleh syariat itu sendiri.
Gugatan Moral terhadap Nikah Siri dan Objektifikasi
Luka lain yang kerap luput dari gegap gempita Hari Ibu adalah praktik nikah siri yang kian marak digunakan sebagai jalan pintas legalisasi syahwat. Banyak perempuan terjebak dalam pernikahan yang tidak tercatat secara negara, yang dalam praktiknya sering kali hanya menempatkan perempuan sebagai objek pemuas nafsu tanpa jaminan hak-hak hukum yang jelas.
Secara fikih formal, nikah siri mungkin memenuhi rukun minimalis, namun secara moral-sosial ia sering kali gagal mewujudkan (kemaslahatan. Tanpa perlindungan negara, seorang Ibu yang dinikah siri tidak memiliki posisi tawar saat terjadi kekerasan atau penelantaran ekonomi. Ia tidak memiliki akses hukum untuk menuntut nafkah bagi dirinya maupun identitas bagi anak-anaknya.
Nikah siri sering kali menjadi alat bagi laki-laki untuk melarikan diri dari tanggung jawab sebagai pelindung/pemimpin. Jika kita benar-benar ingin memuliakan Ibu, kita harus menentang segala bentuk ikatan yang merendahkan martabat perempuan menjadi sekadar objek seksual sementara. Memuliakan Ibu berarti memastikan ia memiliki legalitas yang kuat agar ia tidak dibuang begitu saja saat sang suami merasa bosan atau enggan bertanggung jawab secara finansial.
Nikah siri sering menjadi alat laki-laki untuk lari dari tanggung jawab sebagai pelindung. Islam secara tegas memberikan mandat kepemimpinan yang berbasis perlindungan, bukan penindasan, sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 34:3
“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari har4tanya…” (QS. An-Nisa: 34)
Ayat ini sering kali disalahpahami sebagai lisensi untuk mendominasi. Padahal, kata pelindung dalam ayat tersebut menuntut tanggung jawab penuh, termasuk memberikan nafkah dan perlindungan keamanan. Sangat ironis jika seorang suami menuntut layanan seksual namun membiarkan istrinya bekerja keras sendirian sebagai tulang punggung keluarga tanpa dukungan moral maupun materi.
Ibu sebagai Tulang Punggung dalam Kepungan KDRT
Di luar persoalan hukum, kita juga harus jujur melihat data sosial kita. Dewasa ini, banyak perempuan yang menyandang status Ibu sekaligus menjadi tulang punggung utama keluarga di tengah keberadaan suami yang sehat secara fisik namun abai secara moral. Banyak Ibu yang harus memeras keringat menjadi buruh cuci, pedagang pasar, hingga pekerja migran karena sang suami tidak memahami hak dan kewajibannya.
Dalam tafsir patriarki yang sempit, agama sering kali hanya digunakan untuk melegitimasi posisi laki-laki sebagai pemuas nafsu seksual, tanpa memenuhi kewajiban nafkah. Perempuan dipaksa menjadi “superhuman” yang menanggung beban ekonomi sekaligus domestik, sementara hak-hak emosionalnya diinjak-injak. Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), baik fisik maupun verbal, menjadi hantu yang nyata. Rumah yang seharusnya menjadi oase ketenangan (sakinah), bagi banyak perempuan justru berubah menjadi penjara yang penuh teror.
Islam modern harus tegas menyuarakan bahwa pernikahan bukan kontrak perbudakan. Rasulullah SAW mencontohkan bahwa suami terbaik adalah yang paling lembut dan paling baik perlakuannya kepada istrinya. Membiarkan perempuan bekerja sendiri memenuhi kebutuhan keluarga sementara suami berpangku tangan adalah bentuk kezaliman nyata yang dikutuk agama. Bakti seorang anak dan penghormatan seorang suami—seharusnya mewujud dalam bentuk meringankan beban, bukan menambah derita.
Menembus Komodifikasi dalam Mengembalikan Bakti ke Akar Ibadah
Salah satu ancaman nyata bagi makna Hari Ibu di era digital adalah komodifikasi perasaan. Industri kapitalis dengan cerdik membungkus kasih sayang dalam paket-paket konsumsi. Akibatnya, ukuran “bakti” perlahan bergeser dari nilai substansial—seperti kehadiran fisik dan ketenangan batin menjadi nilai material. Ada bahaya yang mengintai di balik peringatan setahun sekali ini, perasaan sudah “selesai” menunaikan kewajiban setelah mengunggah foto manis di media sosial.
Pandangan Islam modern mengajak kita untuk melihat melampaui estetika digital tersebut. Memuliakan Ibu adalah sebuah marathon(perjalanan panjang), bukan sprint(bukan kecepatan sekali selesai). Ia adalah tentang konsistensi dalam kesabaran saat menghadapi masa tua mereka, kelembutan dalam bertutur kata dan keberanian untuk membela hak-hak mereka di depan publik. Seorang Ibu yang sedang berjuang melawan trauma pelecehan atau Ibu yang kelelahan karena beban ganda, tidak membutuhkan kado mahal yang hanya memberikan kesenangan sesaat. Mereka membutuhkan kehadiran, pengertian dan sistem yang menjamin keamanan mereka.
Menuju Perlindungan yang Utuh dan Berkeadilan
Menggugat seremoni Hari Ibu berarti kita menolak perempuan ditempatkan hanya sebagai objek. Perempuan bukan sekadar objek pemuas syahwat, bukan sekadar mesin pencetak anak dan bukan sekadar “tambal sulam” ekonomi keluarga. Mereka adalah subjek hukum dan subjek spiritual yang setara di hadapan Tuhan.
Agar pemuliaan ini tidak berhenti di bibir saja, kita membutuhkan transformasi nyata:
- Transparansi dan Ketegasan Hukum:Institusi pendidikan agama harus memiliki mekanisme perlindungan santri yang kuat. Tidak boleh ada perlindungan pengampunan bagi pelaku kekerasan seksual, terlepas dari apa jabatannya di pesantren atau organisasi keagamaan bahkan pemerintahan serta pejabat publik.
- Reposisi Peran Laki-laki:Pendidikan pranikah harus menekankan bahwa menjadi suami berarti menjadi pelindung yang siap berbagi beban, bukan sekadar menuntut layanan seksual. Pendidikan pranikah sangat diperlukan dari berbagai agama, bukan hanya wejangan, tetapi benar-benar dilakukan oleh calon keluarga, penerapan, pemahaman hukum serta agama.
- Penguatan Hak Konstitusional:Negara harus mempersempit celah nikah siri yang eksploitatif dan memastikan UU TPKS (Penghapusan Kekerasan Seksusal) diimplementasikan hingga ke tingkat akar rumput tanpa hambatan budaya atau tafsir agama yang bias.
Merdeka dari Sekat Sebagai Hari Besar
Mari kita ubah paradigma kita. Jangan biarkan bakti kita kepada Ibu layu bersama gugurnya bunga yang kita berikan di tanggal 22 Desember. Kemuliaan seorang Ibu terlalu besar untuk dikerdilkan dalam satu hari saja. Hari Ibu seharusnya menjadi momentum refleksi nasional. Sejauh mana kita telah memanusiakan Ibu kita di tengah hiruk-pikuk ambisi pribadi? Apakah kita sudah memberikan waktu yang berkualitas atau hanya memberikan sisa-sisa dari kelelahan kita?
Dalam Islam, setiap hari adalah “hari raya” bagi Ibu. Setiap pagi saat kita bangun adalah kesempatan untuk mencari rida Tuhan melalui senyumannya. Setiap malam adalah waktu untuk memastikan ia tidur dalam keadaan aman dan tenang. Kita butuh aksi nyata yang melindungi perempuan dari kekerasan dan pelecehan, bukan sekadar puisi tahunan yang hambar.
Karena pada akhirnya, surga yang berada di bawah telapak kaki Ibu tidak akan pernah bisa dicapai oleh mereka yang membiarkan kaki itu terus berjalan di atas duri ketidakadilan. Sudah saatnya kita memerdekakan bakti dari sekat kalender dan memanusiakan perempuan sebagaimana Tuhan memuliakannya.