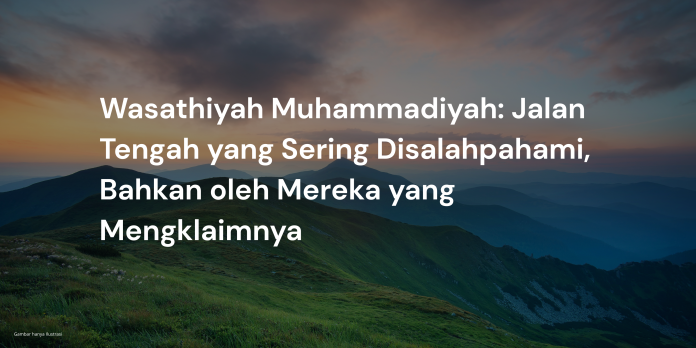Oleh : Rokhmat Widodo
Wasathiyah kerap dielu-elukan, tetapi jarang dipahami secara utuh. Ia disebut di mimbar, ditulis di spanduk, dan dipamerkan sebagai identitas, namun sering direduksi menjadi sikap aman—tidak tegas ke mana-mana, tidak jelas membela siapa. Dalam konteks Muhammadiyah, penyempitan makna ini justru berbahaya. Sebab wasathiyah bukan zona nyaman, melainkan posisi etis yang menuntut keberanian intelektual dan konsistensi moral.
Muhammadiyah tidak lahir dari kecenderungan untuk mencari jalan selamat. Sejak awal, gerakan ini berdiri di tengah badai: melawan praktik keagamaan yang membeku sekaligus berjarak dari arus modernitas yang menanggalkan nilai. Wasathiyah Muhammadiyah adalah sikap sadar untuk tidak terjebak dalam dua ekstrem itu. Ia bukan sikap ragu-ragu, melainkan pilihan ideologis yang berpijak pada tauhid, akal sehat, dan kemaslahatan manusia.
Masalahnya, dalam perkembangan mutakhir, wasathiyah sering dijinakkan. Ia diperlakukan sebagai alat peredam konflik, bukan sebagai kerangka kritik. Padahal, dalam tradisi Muhammadiyah, jalan tengah justru bersifat aktif dan korektif. Tajdid—sebagai jantung gerakan—menuntut keberanian untuk membongkar yang mapan dan membangun yang relevan. Wasathiyah tanpa tajdid hanya akan menjadi moderasi kosmetik: tampak rukun, tetapi miskin daya ubah.
Secara metodologis, Muhammadiyah menolak cara beragama yang hanya bertumpu pada literalitas teks tanpa nalar, sekaligus menolak kebebasan tafsir yang tercerabut dari rujukan wahyu. Di titik inilah wasathiyah bekerja sebagai disiplin berpikir. Ia menjaga keseimbangan antara kesetiaan pada sumber ajaran dan kepekaan terhadap konteks sosial. Sikap ini menegaskan bahwa moderasi bukan berarti mengurangi prinsip, tetapi menempatkan prinsip secara proporsional.
Dalam ranah kebangsaan, wasathiyah Muhammadiyah kerap berada dalam posisi yang tidak populer. Ia menolak politik identitas yang memanipulasi agama, namun juga tidak tunduk pada logika kekuasaan yang ingin mensterilkan nilai moral dari ruang publik. Muhammadiyah memilih jalur keumatan yang kritis—hadir mengoreksi, bukan menguasai. Di sini, jalan tengah justru menjadi posisi yang paling sulit, karena ia berhadapan dengan tekanan dari dua arah sekaligus.
Wasathiyah juga diuji dalam praktik sosial. Ketika agama direduksi menjadi simbol, Muhammadiyah menjawabnya dengan kerja nyata melalui pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Amal usaha bukan sekadar instrumen organisasi, melainkan ekspresi teologis. Islam diterjemahkan menjadi layanan, bukan sekadar slogan. Inilah wasathiyah yang membumi: tidak sibuk menghakimi, tetapi konsisten memecahkan masalah.
Namun tantangan terbesar wasathiyah hari ini datang dari dalam. Ketika moderasi hanya diulang sebagai jargon, ia kehilangan daya kritisnya. Ketika jalan tengah dimaknai sebagai sikap “jangan ribut”, ia berubah menjadi pembenaran atas ketidakadilan. Muhammadiyah dituntut untuk menjaga wasathiyah agar tetap bernyali—berani menyebut yang keliru sebagai keliru, meski datang dari arus mayoritas.
Pada akhirnya, wasathiyah Muhammadiyah bukan strategi bertahan, melainkan etika perjuangan. Ia tidak menjanjikan tepuk tangan, tetapi menawarkan keberlanjutan. Di tengah dunia yang semakin bising oleh ekstremisme dan kepalsuan moral, jalan tengah ala Muhammadiyah justru menjadi posisi paling radikal: setia pada nilai, jernih dalam nalar, dan tegas dalam keberpihakan pada kemanusiaan.